PUKUL SEPULUH MALAM, Taipei sudah senyap. Saya mendapati diri di antrean Seven-Eleven, menimang makanan instan di tangan sambil menghitung koin kembalian dari kereta bawah tanah. Pekerja konstruksi tumpah dari bangunan separuh jadi, mengelap keringat sembari menyusun rencana perjalanan pulang. Kedai kopi terkunci rapat di balik teralis, apartemen berangsur remang di balik gerbang besinya yang tinggi.
Pada saat itulah Ichiko Aoba menyapa saya. Suaranya merayap dari ponsel menuju headphone, dialirkan oleh algoritma YouTube. “What the hell am I doing here?” ucapnya. “I don’t belong here.”
Saya tidak tahu ia pernah memainkan ulang lagu Creep. Lagu itu telah lama saya tinggalkan, jauh dalam bayang-bayang amarah masa remaja. Namun Aoba menyanyikannya dengan berbeda. Tak seperti versi asli dari Radiohead yang sengit, Aoba bernyanyi dengan lirih. Versinya tenang, penuh penerimaan, seolah tak meminta perhatian.
Pada rekaman live yang saya dengar berulang kali, kerumunan terus berceloteh dan bahkan berjalan melewati panggung, tetapi Aoba bergeming. Ia tetap dalam senandungnya.
KEESOKAN HARINYA, saat saya bersiap berangkat menuju pagelaran pameran yang seharusnya saya liput, lagu itu datang kembali. Menyapa saya, seolah memaklumi perasaan terasing saya di tempat ini.
Rombongan saya terdiri dari kritikus dan seniman asal berbagai negara Asia Tenggara. Kunjungan pertama kami, ke studio sebuah kolektif teater independen, dimulai dengan menonton film eksperimental tentang erotisme ruang mandi umum yang dinikmati sepenuhnya dengan VR Goggle. Pada sesi bedah karya, sang sutradara menunjukkan fasilitas teater negara yang mereka gunakan untuk lokakarya, peramuan karya, dan perekaman.
Kami terpana. Billy, kolega saya asal Thailand, berseloroh bahwa kolektif teater di negaranya harus tampil di gedung terbengkalai yang tak layak guna, dan latihan di kafe milik teman-teman.
Saya menangkap kekaguman dan keheranannya. Pekerja seni di Asia Tenggara mesti terus menerus menyiasati tekanan dan kekurangan. Salah satu dari rombongan kami harus menulis dengan nama samaran agar tidak diburu junta di negara asalnya. Kolega lain menghadapi diskriminasi rasial yang dilanggengkan hukum, harus menanggung anak bekas diktator yang dilantik jadi presiden, dan ngeri-ngeri sedap setiap ada kegiatan yang kritis terhadap keluarga kerajaan. Mereka bekerja sebagai pegawai negeri atau arsitek lanskap, dan bercanda soal merampok bank guna membiayai tulisan-tulisannya.
Corrie, kolega saya dari Singapura, menggambarkan praktik artistik kami sebagai kerja pemetaan dan fasilitasi modal sosial. Seni sebagai penengah kepentingan. Bagi kami, berkesenian berarti hidup adu banteng dengan keterbatasan. Gagasan bahwa sebuah kolektif independen bisa memiliki selusin VR Goggles, menerima gelontoran dana dari pemerintah, dan mendapat akses penuh ke gedung teater kelas dunia terasa seperti mimpi di siang bolong.
Jurang ini pun terasa dalam percakapan perihal tema dan gagasan karya. Penampilan teater, pertunjukan, dan tari yang kami hadiri melulu memukau kami dengan tata panggung, lampu, dan penguasaan teknik yang gemilang. Namun, memasuki hari kedua, saya merindukan penyampaian cerita dan gagasan yang berakar dan tidak hanya terjadi di awang-awang.
Salah satu pertunjukan musikal-teater yang kami mampiri, misalnya, datang dengan judul spektakuler “Perjalanan Menuju Akhir Dunia” dan berjanji hendak mengeksplorasi ansietas akhir zaman melalui olah tubuh dan lagu. Namun, ia mentok pada simbolisme yang klise (dua anak dikejar seorang pria berseragam, barisan orang menyusun kotak di pabrik) dan pemilihan musikal yang bikin jidat berkerut.
Lagu yang dimainkan, rupanya, adalah versi jazz dari Winterreise karya komponis klasikal Franz Schubert, dengan libretto berbahasa Taiwan. Tak ada alasan mendalam yang diberikan soal mengapa Schubert yang dipilih, selain bahwa sang pemrakarsa pertunjukan kebetulan menyukai karya-karya Schubert.
Upaya dialog yang terbata-bata paling tidak dibuka oleh Barefeet Dance Theatre, sebuah kolektif yang menampilkan pertunjukan tari di hari kedua. Sebelum acara, mereka mengafirmasi hutang artistik pada masa residensi mereka di pulau Jawa dengan memainkan video penari kuda lumping berlatih di sanggar.
Penampilan tari mereka, yang rancak dan menguras tenaga, memukau tetapi hampir tak sedikitpun menyisakan bayang-bayang tarian Jawa. Di akhir pertunjukan, salah seorang kolega saya menepuk pundak saya dengan seringai lebar dan bertanya, “Jadi, gimana rasanya jadi subyek eksotis?”
Saya memilih angkat tangan. Pertanyaan-pertanyaan ini malah lebih mudah kami hadapi, ketimbang murni menimbang karya-karya seperti itu secara estetis. Boleh jadi, keadaan politik yang genting di negara masing-masing membuat rombongan kami sulit menikmati keindahan yang tercerabut dari kesemrawutan – bahkan dalam karya seni sekalipun.
Kami tidak dapat melihat indahnya daun ditimang angin tanpa menyadari bahwa hutan tempat daun itu berada sedang diancam penggusuran. Kami tidak mampu menikmati deburan ombak yang semilir tanpa mengenang tsunami yang melalap pemukiman di pesisir itu. Setiap jengkal keindahan, bagi kami, bertautan dengan malapetaka, dan setiap detik fantasi, mau tidak mau, akan dipatahkan oleh realita.
Tak ada yang menyampaikannya dengan lebih arif ketimbang Chayanin, rekan saya asal Thailand, yang mengibaratkan masalah ini dengan berkelakar bahwa film meditatif seperti Perfect Days atau Before Sunrise tidak bisa dibikin di Asia Tenggara.
“Nanti jadinya tidak romantis,” katanya sambil terpingkal-pingkal. “Mereka ingin jalan kaki, tapi trotoarnya dimakan pedagang kaki lima. Mereka meminta puisi dari penyair jalanan, tapi penyair itu menjambret tas mereka!”









SABAN MALAM, kami pulang ke penginapan dengan benak penuh pertanyaan ketimbang jawaban. Kami menemukan suaka masing-masing. Kontingen Filipina, misalnya, kelayapan ke pasar malam dan merontokkan rencana diet mereka. Sebagian lain berjalan kaki keliling kota, berharap dapat memahami kota ini dengan melihatnya lebih dekat.
Saya pensiun ke kamar penginapan dan menyalakan lagu, sebab saya tahu kawan lama saya sedang menunggu di sana. “I’m a creep,” nyanyi Ichiko Aoba dari ponsel saya, seolah menyapa. “I’m a weirdo. What the hell are we doing here? We don’t belong here.”
Namun serupa kencan pertama, Taiwan tak lekas menyingkap tabirnya. Ia melulu hadir di hadapan kami sebagai negara yang teratur, dengan kesenian yang megah dan fasilitas pertunjukan yang kelas dunia. Namun, dalam momen-momen lengah, kendali itu lepas dan kemanusiaannya timbul.
Pada The Book of Lost Words, sebuah performans publik yang diampu Against Again Theatre, para peserta diajak berjalan kaki mengelilingi situs-situs bersejarah di kota Taipei sembari mendengar rekaman kesaksian, cerita pribadi, dan arsip bunyi dari para penyintas White Terror – julukan untuk masa pembantaian terhadap penentang pemerintah Chiang Kai-Shek selama dekade 1950-an hingga 1980-an.
Setiap tempat yang kami kunjungi kini sudah disulap menjadi taman kota, terowongan bawah tanah, lapangan bisbol, dan bahkan museum waduk. Namun pada masa White Terror, tempat-tempat ini pernah menjadi penjara, ruang interogasi, bahkan tempat eksekusi.
Suatu ketika dalam perjalanan itu, kami diundang untuk duduk merenung di antara dinding lembab waduk kota Taipei – yang konon pernah dialihgunakan sebagai ruang interogasi. Dari rekaman suara, kami mendengar kesaksian seorang pekerja pabrik yang ditangkap aparat beserta rekan-rekannya sebab dituduh mengorganisir protes. Atasan mereka disekap duluan, lantas menghilang di ruang interogasi selama berhari-hari. Persis sebelum ia dieksekusi, ia meludahkan secarik kertas kosong: sebuah pesan kepada teman-temannya bahwa sepanjang interogasi ia tidak mengatakan apa-apa.
Ketika cerita itu tiba di klimaks, salah seorang pemandu tur dari Against Again Theatre menghampiri kami dengan cawan berisi kertas kosong, membagikannya pada setiap peserta, dan mendekatkan telunjuknya pada bibirnya. Kami menanggung cerita ini dalam senyap, ia seolah berkata, dan sekarang rahasia ini adalah rahasiamu juga.
Kesenian, dalam narasi yang saya pahami di Indonesia, seharusnya adalah ruang bagi kebenaran dan otentisitas untuk mengemuka. Gagasan utopisnya begini: ketika jurnalisme dibungkam, sastra berbicara. Ketika kritik dan narasi pinggiran diabaikan, maka kesenian mengangkat suara mereka.
Sedikit banyak, hal sebaliknya justru terjadi di Taiwan. Kesenian yang tersaji di hadapan saya di Taiwan, menyadur Brecht, tak menjadi cerminan akan realita maupun palu yang digunakan untuk membentuk kenyataan baru. Kesenian justru menjadi ajang realitas virtual, sebuah upaya soft power untuk menunjukkan imaji akan Taiwan yang mereka harap akan dipercaya oleh dunia.
Di akhir sebuah sesi diskusi dengan budayawan-budayawan asal Taiwan, para panelis menyingkap gagasan ini lewat suatu frasa yang miris: Team Taiwan. Setiap orang di Taiwan – termasuk, tentu saja, para pelaku budayanya – harus kompak berkontribusi dalam pemajuan negerinya dan menunjukkan citra Taiwan yang melulu baik kepada dunia.
Konfrontasi, kritik, perdebatan, dan masalah sosial – semua hal ini cenderung dipinggirkan atau tidak dianjurkan dalam leksikon keseharian Taiwan, sebab akan mencoreng citra Taiwan sebagai negara yang maju, kompak, dan layak didukung.
Seorang panelis menggoda saya begini: Taiwan membuka pintu bagi budayawannya untuk membicarakan era White Terror, sebab pengakuan dosa seperti ini membuat mereka tampak seperti negara yang progresif dan sudah move on dari masa lalu fasis mereka. Namun cobalah membuat karya serupa tentang krisis pekerja migran di Taiwan, dan minimal kamu akan disambut dengan dahi mengernyit.
Seniman di Taiwan boleh membuat karya yang apik tentang White Terror, bahkan bekerjasama dengan museum yang mengingat masa-masa ini. Namun nama Chiang Kai-Shek masih menghiasi Memorial Hall, dan Kuomintang masih jadi partai politik paling dominan di pemilu. Ada keterbukaan, tapi keadilan tidak tuntas. Ada keinginan untuk menjadi kritis akan masa lalu, tapi mereka ragu mempertimbangkan bagaimana masa lalu terus membentuk masa kini dan bahkan masa depan.
Namun saya tak dapat menyalahkan mereka. Panelis itu mengingatkan saya bahwa Taiwan diapit oleh Jepang, Tiongkok, Korea Utara dan Korea Selatan – semuanya negara adidaya yang entah memandang Taiwan sebagai pion dalam percaturan geopolitik global atau sebagai borok yang mesti ditumpaskan. Ekonomi dan taraf hidup mereka mentereng bila dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, tetapi mereka mungil bila disandingkan dengan tetangga-tetangga mereka yang galak.
Kesenian harus mengemban tugas berat: menggalang dukungan dan simpati dunia terhadap Taiwan, sekaligus menunjukkan wajah Taiwan yang indah dan berseri-seri, supaya Taiwan diakui dan diberikan ruang dalam pergaulan global. Setiap seniman, ucap panelis di diskusi kami, secara tidak langsung menjadi duta bagi negeri yang merindukan kawan, menginginkan pengakuan, dan mendambakan keselamatan.
Melalui kacamata ini, saya mengingat kembali pengalaman saya di Taiwan dengan sangat berbeda. Saya tidak lagi merasa menjadi penonton dari aksi unjuk gigi soft power Taiwan. Malah saya memandang bahwa kehadiran kami adalah bagian dari upaya mereka untuk mencari acuan yang berbeda di dunia, untuk membangun ikatan kultural yang lebih dekat dengan Asia Tenggara ketimbang melulu berkutat di Asia Timur yang penuh marabahaya.
Dalam narasi ini, karya kelompok seperti Barefeet Dance Theatre yang mencari-cari tautan antara tradisi tari Taiwan dan Jawa pesisir dapat dipandang sebagai upaya canggung untuk memulai dialog dan keterhubungan. Bahkan performans dengan narasi kritis yang acakadul seperti Perjalanan ke Akhir Dunia dapat dipandang sebagai upaya terbata-bata untuk mengartikulasikan ansietas mereka terhadap posisi Taiwan yang terus menerus terancam.
Mereka tidak sedang pamer. Mereka sedang meminta pengertian kami.
TAKSI MENUJU BANDARA menjemput saya pagi-pagi buta di penginapan. Saya meminta izin menurunkan jendela, menghirup udara pagi, dan menyaksikan Taipei berangsur terjaga dari tidurnya. Sopir taksi saya tersenyum dan memberi usulan tambahan. Sebab pesawat saya masih lama, ia akan menyetir dengan lebih santai.
Dari balik pintu taksi, saya melihat kedai yang sesak akan manusia. Anak-anak sekolah menyeberang jalan berpegangan tangan dengan orang tuanya. Lansia berjemur dengan kursi roda yang didorong pekerja migran. Kabut tipis turun dari pegunungan, menyeberangi lembah dan menyusuri pojokan jalan tol. Taksi saya berhenti di hadapan sederet kompleks apartemen mewah. Gerbangnya besi, tinggi menjulang, dan terpacak di mukanya adalah sebuah stiker yang mengarahkan kita ke tempat perlindungan serangan udara.
Sopir taksi saya menyadari bahwa saya sedang menatap lekat-lekat pada tanda perlindungan serangan udara itu. “Kami semua khawatir tentang masa depan,” ucapnya kepada saya. “Tetapi, ketika kami melihat ke sekitar, semuanya baik-baik saja. Jadi kekhawatiran kami tadi itu sebenarnya berasal dari mana?”
Saya menggelengkan kepala. Ini siksa batin yang berbeda dari yang kami pahami. Saya tahu rasanya menghadapi sensor, aparat, dan himpitan ekonomi. Saya tidak tahu rasanya berkarya di sebuah negeri yang keberadaannya sendiri tak pasti. Negara yang seolah memiliki segalanya, tetapi sewaktu-waktu dapat dihapus dari muka bumi.
Melihat sopir taksi saya terpekur, saya memasang headphone dan mencari lagu. Baru saja menyusuri YouTube, ia sudah menanti. Creep karya Ichiko Aoba. Setelah menghabiskan waktu di Taipei, saya menyambut kedatangannya seperti kawan lama.
Mulanya saya mengira ia hadir untuk meledek saya, menertawakan saya yang terperangah dan tak paham akan Taiwan. Kini saya paham – ia adalah jeritan tersembunyi dari tempat ini. Creep adalah senandung Taiwan untuk dirinya sendiri, dalam perjuangan senyapnya di hadapan dunia yang culas dan penuh kepentingan.
Ketika kami tiba di bandara, sopir taksi saya bersikeras menjabat tangan saya. “Saya harap kamu akan datang lagi,” ucapnya. “Mungkin, kali berikutnya, kamu bisa mengenali rumah kami lebih jauh.” (*)
Ditulis dengan dukungan Arts Equator.
The ArtsEquator Fellowship Critics Network is made possible with the support of Taiwan’s Ministry of Culture and the Taipei Economic and Cultural Office in Malaysia.




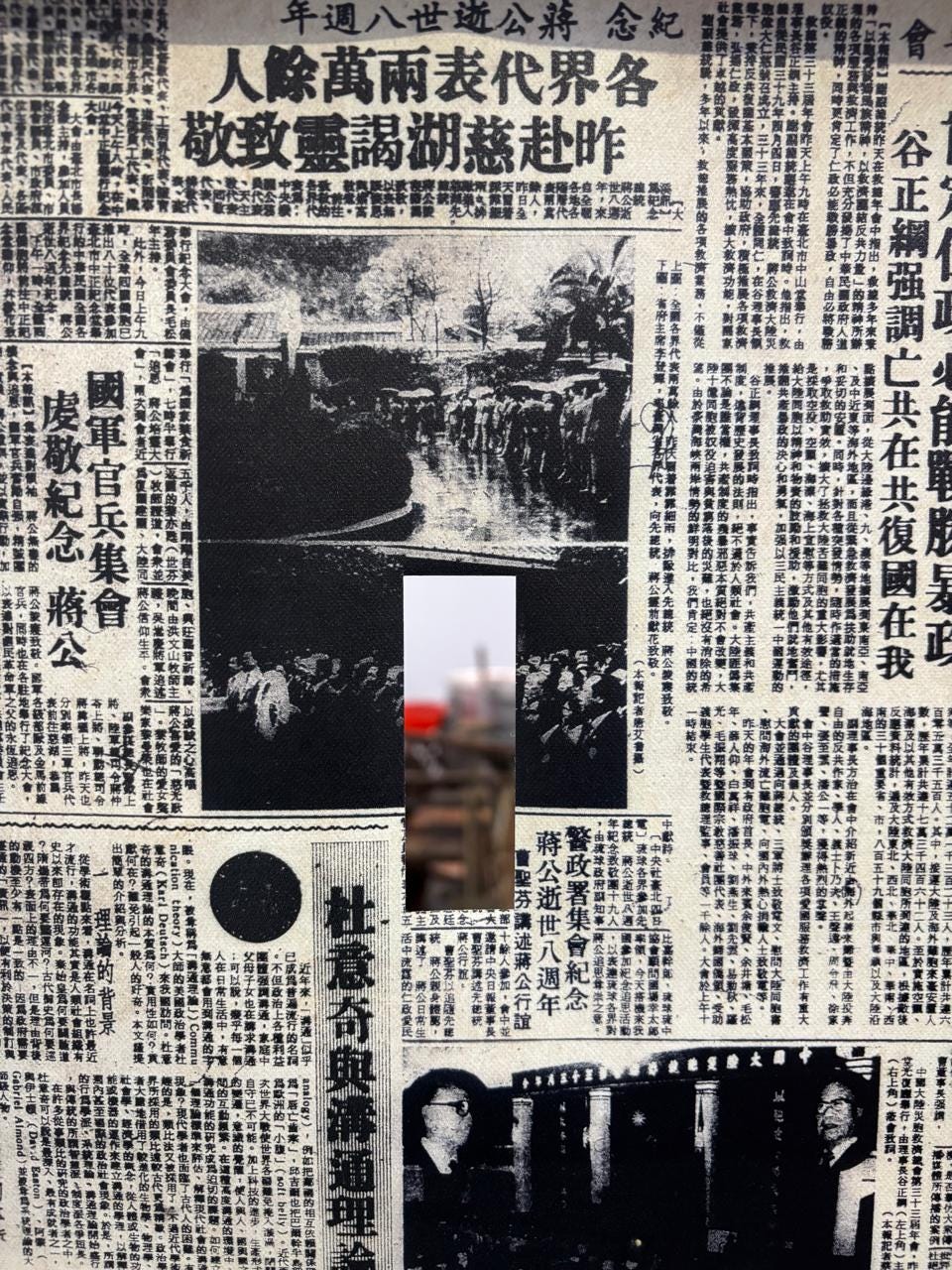

“I can look at a crowd," he said to his friends, "I can just look at it. It's all, uh, very scientific, and I can diagnose the crowd psychologically. Just four of us, properly positioned, can turn the crowd around. We can cure it. We can make love to it. We can make it riot."
Jim's friends looked at him blankly.
"Hey, man," Jim said, "don't you even want to try?”
― Jim Morrison